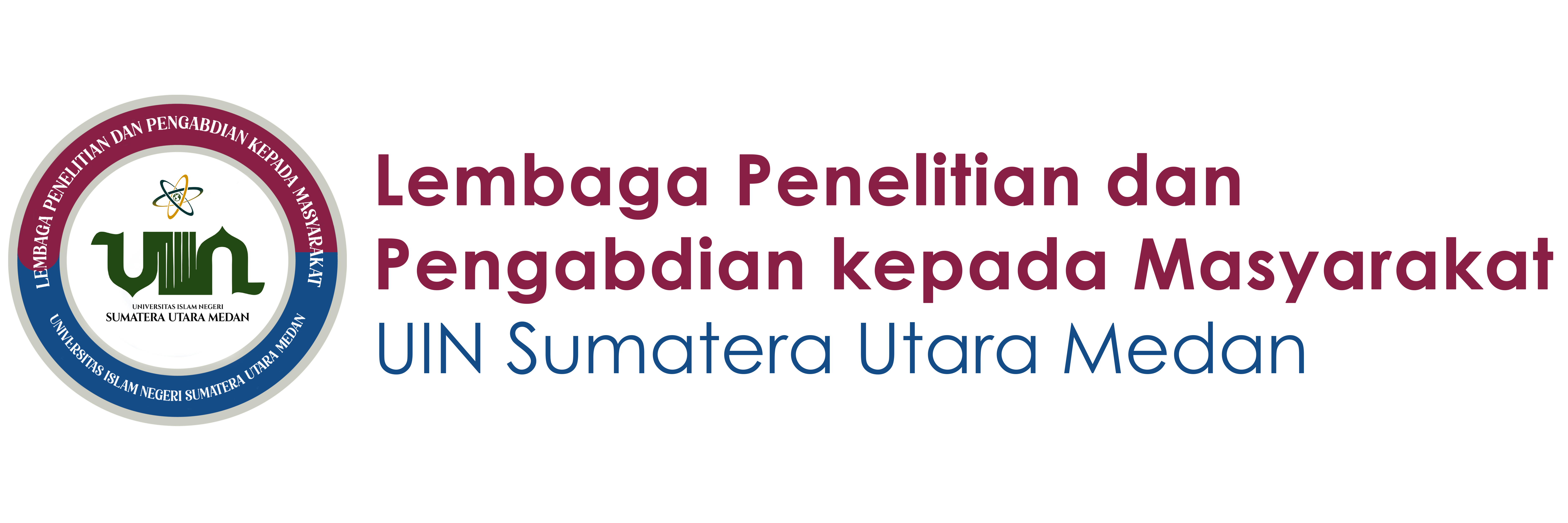Daring/Zoom — Selasa, 23 September 2025
Sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Environmental Crisis, Ecological Degradation, and Sustainable Behavior” menghadirkan empat narasumber lintas negara—Maurits Arif Fathoni Lubis (Nanyang Technological University), Septian Emma Dwi Jatmika, M.Kes (International Health Program, Institute of Public Health, College of Medicine, National Yang Ming Chiao Tung University), Tri Bayu Purnama, S.K.M., M.Med.Sci (Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, 1-757 Asahimachi Dori, Chuo-Ku, Niigata 951-8510, Japan), dan Salianto, M.Psi (Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia)—untuk memetakan sikap, perilaku, norma, hambatan, dan strategi keberlanjutan di wilayah masing-masing. Diskusi dipandu Syafran Arrazy, Ph.D melalui Zoom.
Singapura menempatkan isu lingkungan sebagai arus utama tata kelola kota—mulai dari urban greenery, pembatasan interaksi dengan satwa liar, hingga kedisiplinan publik berbasis regulasi; generasi muda terlihat paling aktif dalam agenda hijau. Taiwan menonjol dengan lingkungan kota yang bersih, pemilahan sampah yang ketat, mekanisme denda berbasis CCTV, serta pelibatan lansia sebagai relawan layanan publik. Jepang mengedepankan pengelolaan sampah yang sistematis, kultur barang second-hand, dan solusi teknologi (termasuk energi nuklir) untuk mengurangi beban emisi. Di Indonesia, dukungan kebijakan sudah tumbuh—termasuk inisiatif ekoteologi Kementerian Agama—namun implementasi di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah.
Di Taiwan, insentif diskon bagi pembeli yang membawa tumbler dan armada truk sampah terpisah (umum, organik/basah, serta kertas/plastik) membentuk kebiasaan baru warga. Di Singapura, harga dan pajak kendaraan yang tinggi, jaringan MRT–bus yang merata, serta ancaman denda—termasuk larangan permen karet—mendorong peralihan ke transportasi publik dan praktik minim sampah; advokasi kampus aktif menggelar lokakarya “bring your own tumbler” dan iuran plastik untuk mendanai kegiatan lingkungan. Jepang menuntut pemilahan detil (hingga minyak jelantah dibekukan sebelum dibuang) dengan jadwal dan sanksi jelas, sementara kultur paperless dan paper-based masih berjalan berdampingan. Di Indonesia, kebiasaan domestik dan ketiadaan “ganjaran-hukuman” konsisten disebut sebagai tantangan perubahan perilaku.
Pendidikan dini muncul sebagai kunci di tiga negara: kunjungan rutin siswa ke taman (Singapura), kampanye berulang di sekolah dan kartu “stempel” aksi hijau (Taiwan), serta pembiasaan antre–buang sampah terpilah sejak usia dini (Jepang). Kombinasi denda + insentif serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dinilai mempercepat adopsi perilaku ramah lingkungan. Indonesia menapaki jalur ekoteologi—nilai keagamaan sebagai dorongan moral—namun dampaknya diperkirakan baru tampak dalam 5–10 tahun mendatang jika pendidikan, penegakan, dan fasilitas publik berjalan selaras.
Para peserta menegaskan peran pemuda sebagai lokomotif gerakan, pentingnya mulai dari tindakan sederhana di rumah, serta perlunya kebijakan yang konsisten dari hulu ke hilir (pendidikan–fasilitas–penegakan). FGD menutup dengan ajakan kolaboratif lintas komunitas dan lintas iman sebagai model praksis moderasi beragama yang pro-lingkungan di Asia.